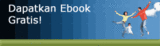Matanya yang nyalang tak percaya pada ucapan. Ia tak bisa memahami hakikat kata yang aneh dan mustahil. Ia tak dapat menelan kebisuannya. Waktu tujuh tahun yang lilin-lilinnya ia padamkan sejak beberapa bulan lalu tak pernah mau menerima air mata mereka. Ia bertanya pada ibunya, yang ketika itu sedang mengatur tempat tidurnya:”Apakah mereka tidur?” Ibunya hanya tersenyum, sekalipun ia sebenarnya terperanjat lalu ia bertanya sambil meneruskan pekerjaannya. ”Kamu berbicara apa?”
”Apakah orang-orang Yahudi membunuh mereka ketika mereka sedang terlelap?”Rona wajah ibunya berubah dalam sekejap, dan dalam keadaan sesak ia berkata:”Kamu tidak perlu memikirkan hal itu, Amru!”
Amru pun berteriak marah:”Ibu selalu berkata bahwa saya harus menjaga kebersihan pakaian. Ibu juga selalu melarang saya jangan memukul orang lain. Selalu begitu.” Dan tangisnya meledak. Seketika ibunya terhenyak. Betulkah ia ini Amru? Bocah yang kalem itu, inikah anaknya? Inilah pertama kalinya ia melihat anaknya bagai badai yang menerpa ranting-ranting kering. Ya Rabbi, bagaimana bocah-bocah bisa menjadi besar dan dewasa dalam usia semuda ini?
Ia menatap nanap wajah anaknya. Anak itu agak menakutkannya. Namun segera ia mengembalikan kenangannya. Lalu tiba-tiba ia berkata lagi:”Mereka melakukan semua yang ibu larang saya melaukannya, dan semua orang mengatakan dirinya pahlawan. Kini saya ingin menjadi pahlawan.”
”Kamu sekarang sudah pahlawan. Buktinya, kamu bisa mengalahkan teman-temanmu di sekolah.”
”Saya mau melontarkan batu seperti mereka. Percayalah, sekarang saya sudah kuat.”
”Lantas, kamu mau melempar siapa?”
Secercah harapan memancar seketika dari matanya ketika sambil meletakkan tas sekolahnya ia berkata dengan yakin:”Orang Yahudi.”
”Disini tidak ada orang Yahudi.”
”Lalu dimana mereka?” Di Palestina.” ”Jauhkah Palestina dari rumah kita?”
Ibunya tersenyum, tapi sekali ini senyumannya tampak getir. Ia pun terduduk di atas ranjangnya dan berkata:”Tidak terlalu jauh.”
”Kalau begitu, berangkat saja kita semua kesana?”
”Tak bisa.”
”Begini saja, Bu. Kakek kita tetap tinggal disini, dan kita berangkat pakai mobil Bapak, pasti muat.”
”Orang Yahudi pasti tidak akan mengijinkan kita masuk kesana.”
Ia mendekati ibunya dan berkata dengan dada yang sesak, sekalipun harapan masih tampak dalam sinar matanya:”Saya benci orangYahudi, mengapa harus minta izin pada mereka?” Ditatapnya wajah anaknya dekat-dekat. Dan ia menemukan air matanya sendiri sedang berkaca-kaca dalam tatapan anaknya. (”Kau benar, Nak. Mengapa kita harus selalu menunggu? Mengapa kita membiarkan mereka memukul kita dan kita menahankan rasa sakitnya? Mengapa setelah ada izin mereka baru kita bertindak?”)
Dengan kedua lengannya ia mendekap anaknya. Ia kemudian membisikkan beberapa patah kata untuk mematikan perasaan dalam diri anaknya, smentara ia mengira dia sendiri telah melupakannya. ”Ibu juga membenci orang Yahudi, Amru. Tetapi lupakan saja mereka, lebih baik kita memikirkan apa yang akan kita lakukan hari ini.”
”Apakah kita akan membiarkan mereka membunuh anak-anak?” ”Mereka tidak akan membunuhnya”. Tiba-tiba Amru berteriak parau, sementara air mata menggenang di pelupuk matanya. ”Saya melihat mereka membunuh anak-anak di televisi.”
Ibunya tampak merasa bersalah. Ia mencela dirinya:”Semestinya saya tidak membiarkan kamu menyaksikan acara itu,”katanya pada dirinya sendiri. Ia pun memungut tas anaknya yang tergeletak di lantai, lalu ia berkata dengan nada agak mengancam:”Sudahlah, nanti kamu terlambat sampai di sekolah.”
Amru kemudian mengambil tasnya sambil keluar kamar. Tapi belum jauh melangkah, tiba-tiba ia berpaling kembali pada ibunya.”Bapak guru bilang, anak-anak itu tidak pergi ke sekolah. Orang Yahudi menutup sekolah-sekolah dan membunuh anak-anak, bukan begitu, Bu?” Ia mendekati ibunya. Seketika nada kalimatnya berubah, suaranya mengiba dan penuh harap: ”Coba kalau Bapak pergi kesana dan membunuh orang-orang Yahudi itu, lalu mengusir mereka. Bu, tolong katakan pada Bapak begitu, ya. Pokoknya Amru berjanji akan menjadi dokter.”
Potongan-potongan kecil kata-kata itu membatu di matanya. Ia pun mendekap anaknya penuh rasa cemas, lalu berkata:”Jangan khawatir, Amru! Disini tak ada orang Yahudi, tidak ada senjata. Pokoknya tak ada orang yang akan mengganggu anak kecil seperti kamu.”
Secepat kilat Amru menarik badannya dari dekapan ibunya. Sambil mengangkat tasnya, ia berkata dengan marah: ”Saya bukan anak kecil lagi, saya bukan pengecut.”
Ia berangkat ke sekolah dan bermain bersama teman-temannya di halaman sekolah. Permainan baru. Bukan mereka yang memilihnya, tapi permainan itulah yang memilih mereka: permainan tentang orang Yahudi dan bocah-bocah pelempar batu. Pada mulanya tak ada yang sudi memerankan orang Yahudi. Akhirnya mereka memutuskan, siapa yang salah membaca surat al-Fatihah, dialah yang akan memerankan orang Yahudi. Tapi tak ada seorang pun salah bacaannya. Akhirnya mereka pun memilih surat-surat lain dan berlomba menghafalnya.
”Orang Yahudi membunuh anak-anak. Allah suka sama anak-anak, kita cinta pada Allah dan benci pada orang Yahudi.” Itulah kata yang diucapkan Amru kepada gurunya, yang hanya bisa berdiri termangu sambil menatap wajah muridnya.
(Mereka mengira telah membabat habis manusia-manusia itu sampai ke akar-akarnya. Tetapi anak-anak justru membuktikan betapa kuatnya akar mereka tertancap ke bumi. Mereka membunuh anak-anak Palestina untuk menciptakan dari tubuh-tubuhnya mata-mata kecil yang menatap tajam kuburannya sendiri.)
Mata gurunya seperti hendak mengatakan:”Kini mereka mulai menggali kuburannya sendiri, kuburan mereka ada di sini, di kedua bola matamu. Andaikata kamu dapat memahami si pembangkang yang kini ada dalam kedua tanganmu yang mungil! Ayo Amru, jadilah engkau batu yang menghantam mereka dari jauh, biarkan mereka mendengarkan teriakanmu. Kamu lebih kuat dari mereka, Amru. Kamu mencintai Allah, dan Allah membenci mereka.”
Malam itu semua orang sudah berada di pembaringan masing-masing. Hanya Amru yang masih duduk di samping bapaknya. Tidak lama kemudian, ibunya datang menegurnya setelah sebelumnya ia berjanji membolehkannya menonton siaran berita di televisi, apa pun resikonya:”Sekarang waktu tidur.”
Amru merasakan ada nada keras dan ngotot dalam ucapan itu. Ia pun berdiri dan berjalan tenang menuju kamar tidur. Sesaat ibunya agak bingung melihat reaksi anaknya. Biasanya ia selalu mengiba kalau menginginkan sesuatu. Tapi sekali ini ia memutuskan memenangkan kemauannya.
Senandung musik yang sangat sentimental menarik perhatian Amru. Ia pun bangun dan merangkak dengan tenang, perlahan-lahan, untuk menyaksikan acara di televisi dari kejauhan. Semua kata yang rumit, dan gambar-gambar, tidak dapat dipahaminya. Baginya itu hanyalah saat kita menunggu datangnya badai.
Perlahan monitor kecil itu membesar di matanya. Membesar dan membesar lagi, tampak seperti raksasa-raksasa, ya serdadu-serdadu itu! Persis seperti yang ada dalam dongeng yang sering diceritakan kakek padanya, sepatu mereka, kepala mereka, dan semua peralatan berat yang mereka sandang.
Sepatu-sepatu mereka, bahkan tangan-tangan mereka, setiap bagian dari semuanya turut mengejar bocah kecil itu. Dan Amru mendengar lolongannya dari kejauhan. Detak jantungnya seperti mengikuti langkah-langkah si bocah. Mereka makin mendekati bocah itu, makin dekat, dan makin dekat, dan akhirnya mereka dapat menangkapnya. Sebuah suara kecil melolong di mata Amru: ”Pak, selamatkan dia, Bapak! Jangan biarkan mereka membunuhnya, Pak!”
Sebuah patung kecil tiba-tiba memajangkan dirinya ke arah Amru. Ia mengambil dan melemparkannya dari kejauhan sambil berteriak sekeras-kerasnya,”Jangan bunuh dia! Jangan bunuh dia!”
Dan tangisnya pun meledak, sementara monitor televisi raksasa itu berubah dalam sekejap menjadi puing-puing yang berserakan di kamar. Semua berlangsung dalam kebisuan, hanya teriakan ibunya yang kemudian mengubah kekagetan bapaknya menjadi ketakutan yang sesungguhnya.
Aliran listrik pun putus, lampu-lampu padam, seketika rumah menjadi gelap. Bapaknya berteriak sambil mencarinya dalam kegelapan:”Amru! Amru!”
Dari dalam kegelapan Amru berseru:”Saya telah membunuhnya. Bapak sudah lihat’kan? Saya bisa membunuhnya’kan? Darah hitam mereka kini membanjiri rumah kita. Orang Yahudi darahnya hitam, Pak!”
Bapaknya mendekapnya dengan kuat, sementara Amru masih terus mengulang-ulang ucapannya: (Orang Yahudi darahnya hitam! Darahnya hitam! Hitam! Hitam!)
sumber:Jihad al-Rajbi. Li Man Tahtamil al-Rashshah. Filistin Muslimah, 1993. Terjemahan Anis Matta. Penerbit: Pustaka Firdaus dan Yayasan Sidik, 1995.